Palembang, Sumselpost.co.id – Sejarawan dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. Dedi Irwanto, M.A., konsep “Sapatha” dalam perspektif teori dan nilai historisnya.
Dalam prasasti-prasasti peninggalan Kedatuan Sriwijaya, “sapata” atau “sapatha” merujuk pada sumpah atau kutukan yang ditujukan kepada mereka yang melanggar aturan atau berkhianat terhadap kerajaan. Sapatha merupakan bagian dari sistem hukum dan digunakan sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kerajaan Sriwijaya.
Menurutnya, sapatha bukan sekadar istilah, melainkan sebuah ideologi yang memiliki akar dalam sejarah yang panjang terutama di Palembang.
“Sapatha memiliki kontinuitas dari dulu hingga sekarang , yang merupakan simbol kedamaian dan kesejahteraan. Di masa kini, sapata juga dapat dilihat dalam bentuk sumpah jabatan yang diambil oleh para pejabat,”kata Dedi saat menjadi narasumber dalam seminar hasil kajian koleksi Museum Sriwijaya , Prasasti-Prasasti Sapatha Sriwijaya dan Fragmen Kapal Sriwijaya di UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya (TWKS) , Gandus, Palembang, Rabu (9/7/2025) dengan moderator oleh pecinta sejarah kota Palembang Rd Moh Ikhsan.
Dedi mengungkapkan bahwa ketika membahas sapatha, ia merasakan ketakutan untuk menjadi pejabat.
Ketakutan ini muncul karena adanya keyakinan akan kutukan yang menyertai sapatha.
Penangkapan mantan Walikota Palembang Harnojoyo dalam kasus penghancuran Pasar Cinde oleh Kejari Sumsel bisa jadi menurutnya dianggap sebagai manifestasi dari kutukan tersebut, di mana tindakan korupsi membawa konsekuensi negatif bagi pelakunya.
Sehingga menurutnya perlunya pejabat publik untuk memahami dan menghayati sapata dalam menjalankan tugas mereka. Integritas dan komitmen untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Namun, ia menemukan bahwa kutukan sapatha di Sriwijaya tidak hanya ditujukan kepada mereka yang melakukan kejahatan.
Sebaliknya, ada juga kutukan yang membawa berkah, yang dapat meningkatkan derajat seseorang.
Dalam konteks ini, ia merujuk pada istilah dalam agama Buddha, di mana seseorang yang berbuat baik dapat disebut berwajah syarira, yang berarti memiliki tubuh dan pikiran yang murni.
Lebih lanjut, Dedi membandingkan konsep sapatha dengan ajaran Sufi dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa dalam perjalanan spiritual, seseorang harus melalui tahapan syariat, tarikat, hakikat, dan akhirnya makrifat. Ketika seseorang mencapai makrifat, pemahaman dan pandangannya akan terbuka, memungkinkan mereka untuk melihat kebenaran yang lebih dalam.
Dedi merasa terdorong untuk memperdalam pemahaman Islamnya, salah satunya dengan mempelajari Sufi.
Ketua Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan (Puskass) ini menekankan bahwa pencapaian spiritual yang baik tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga dapat memakmurkan masyarakat secara keseluruhan. Ia menyatakan bahwa jika seseorang berbuat baik, maka akan ada dampak positif yang dirasakan oleh banyak orang.
Ia menekankan pentingnya integritas dan komitmen dalam melaksanakan amanah yang di emban.
Dengan pemikiran ini, Dedi Irwanto berharap agar konsep sapatha dapat menjadi landasan bagi para pejabat untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, serta mendorong masyarakat untuk berperilaku baik demi kemakmuran bersama.
Sedangkan peneliti ahli muda , kelompok riset Epigrafi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (Brin) yang juga Ketua Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia (PAEI) Wahyu Rizky Andhifani melihat sapatha dalam konteks kekuasaan Sriwijaya merupakan perangkat politik sakral yang dirancang untuk menanamkan ketundukan totoal dan mengendalikan potensi pemberontakan melalui mekanisme kutukan yang bersifat kolektif dan transenden.
Kutukan tidak hanya diarahkan pada individu pembangkang tapi meluas hingga ke keluarga dan keturunannya menandakan logikan hukuman yang menghapus identitas sosial –politik pelaku secara menyeluruh.
Dalam teks-teks sapatha, pelanggaran terhadap datu tidak hanya dimaknai sebagai tindakan melawan negara tetapi sebagai dosa kosmik yang mengganggu tatanan spiritual sehingga balasannya pun bersifat mistis –melalui sakit, kegilaan , kematian dan kejatuhan moral,
“ Kehadiran sapatha menunjukkan bahwa Sriwijaya menjalankan kekuasannya bukan hanya secara administrasi atau militer melainkan melalui sistem hukum yang performatif dimana kata-kata menjadi alat control dan ketundukan dipastikan oleh ancaman metafisik yang terus hadir melalui prasasti.
Sedangkan Arkeolog dari Peneliti BRIN Sondang Martini Siregar menjelaskan kenapa Kedatuan Sriwijaya banyak mengeluarkan prasasti kutukan.
“Prasasti kutukan itu adalah sebagai pernyataan kekuasaan dan mempertegas otoritas datu di mata rakyat dan pejabat kerajaan. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi ini adalah pernyataan kekuasaan dan otoritas,”katanya.
Selain itu ada cerminan kekhawatiran penguasa Sriwijaya terhadap pemberontakan atau pengkhianatan daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Sriwijaya.
Dan mencegah pemberontakan, pengkhianatan, persekongkolan untuk melawan kekuasaan Sriwijaya.
Menurutnya kutukan dianggap efektif untuk menekan gejolak dalam kerajaan sehingga memudahkan Sriwijaya memperluas atau mempertahankan wilayahnya.
“Kalau kita pelajari di situ bahwa ada orang yang berkhianat, yang tidak setia, atau dia memberikan atau membujuk atau merayu orang berkhianat juga kepada penguasa, dia juga kena kutuk. Bukan hanya dia, tetapi keluarganya juga kena kutuk. Di sini yang begitu seremnya otoritas dan kekuasaan kerajaan Sriwijaya,”katanya.
Selanjutnya, ancaman kutukan dalam prasasti bukan sekadar sanksi duniawi, melainkan juga bersifat sakral, melibatkan sumpah di hadapan dewa-dewa.


















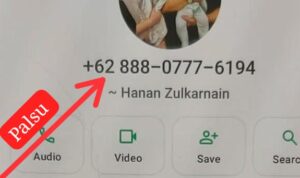
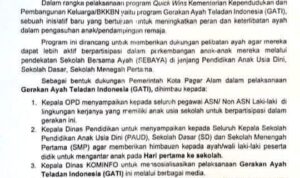






Komentar