Palembang, Sumselpost.co.id- Perang dagang global telah menciptakan ketimpangan struktural yang semakin memperlebar jurang sosial-ekonomi antarnegara dan antarkelompok sosial.
Salah satu pemicu utamanya adalah kebijakan proteksionis yang diambil oleh pemerintahan Donald Trump, khususnya melalui peningkatan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang utama, yang memicu reaksi serupa dan eskalasi konflik dagang global.
Fenomena ini berdampak pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek pengurangan kemiskinan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kajian ini mengkaji bagaimana sistem ekonomi berbasis nilai sosial dapat berperan dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak ketidakpastian ekonomi global.
Dengan pendekatan sosiologis dan analisis literatur, kajian ini menunjukkan bahwa ekonomi berbasis solidaritas sosial, distribusi yang adil, dan etika produksi serta konsumsi memiliki potensi besar dalam menciptakan struktur sosial yang lebih tangguh. Kajian ini juga menekankan pentingnya penguatan jejaring sosial, kelembagaan lokal, dan norma kolektif sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan.
Perubahan arah kebijakan ekonomi global selama dekade terakhir telah menimbulkan dinamika baru dalam sistem perdagangan internasional.
Salah satu titik balik yang signifikan adalah kebijakan proteksionis yang diadopsi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, selama masa jabatannya (2017–2021) dan berlanjut di episode kedua tahun 2025. Di bawah slogan “America First”, pemerintahan Trump mendorong strategi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan domestik dengan menargetkan neraca perdagangan bilateral, terutama terhadap Tiongkok. Kebijakan tersebut secara langsung diwujudkan melalui serangkaian peningkatan tarif impor terhadap produk-produk dari Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, dan mitra dagang lainnya.
Dalam beberapa minggu terakhir bulan Maret di tahun 2025 , tensi ekonomi global meningkat seiring kebijakan proteksionis yang diberlakukan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Kebijakan seperti peningkatan tarif impor terhadap produk Tiongkok dan negara-negara mitra dagang lainnya, yang dikenal luas sebagai bagian dari strategi America First, menjadi pemicu eskalasi perang dagang global.
Ketegangan ini telah mengganggu stabilitas perdagangan internasional, memperlemah pertumbuhan ekonomi, dan berdampak pada negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor serta keterbukaan pasar global. Kebijakan ini kemudian dibalas dengan tindakan serupa oleh negara-negara terdampak, yang memunculkan fenomena yang dikenal sebagai perang dagang. Ketegangan perdagangan yang sebelumnya bersifat teknis berubah menjadi isu politik-ekonomi global, memengaruhi harga komoditas, investasi lintas negara, dan stabilitas ekonomi di negara-negara berkembang.
Dampak dari perang dagang ini tidak hanya terlihat pada penurunan volume perdagangan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, tetapi juga membawa konsekuensi sosial yang serius. Di banyak negara berkembang, krisis perdagangan memicu pemutusan hubungan kerja, penurunan ekspor, dan berkurangnya pendapatan negara.
Semua ini secara langsung maupun tidak langsung menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak (SDG 8), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10).
Kebijakan-kebijakan mana mencerminkan pendekatan ekonomi nasionalistik yang berdampak luas terhadap struktur sosial-ekonomi global, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada perdagangan luar negeri.
Dalam konteks ini, kajian mengenai alternatif sistem ekonomi berbasis nilai sosial menjadi semakin penting untuk memahami ketahanan sosial masyarakat terhadap tekanan eksternal semacam ini. Untuk memperjelas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Trump yang relevan terhadap isu perang dagang, berikut disajikan ringkasan beberapa kebijakan kunci dan dampaknya:
Kebijakan Ekonomi Era Donald Trump yang Berkaitan dengan Perang Dagang
No. Kebijakan Deskripsi Dampak Sosial-Ekonomi
1 Peningkatan Tarif Impor terhadap Tiongkok (2018–2020) Tarif diberlakukan terhadap lebih dari US$ 360 miliar barang dari Tiongkok Kenaikan harga barang konsumsi, ketegangan diplomatik, dan disrupsi rantai pasok global
2 Penarikan AS dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) Menolak perjanjian perdagangan multilateral yang melibatkan 12 negara Asia-Pasifik Melemahkan posisi AS dalam kerjasama dagang internasional dan menguatkan proteksionisme
3 Revisi NAFTA menjadi USMCA Meningkatkan proteksi untuk industri dalam negeri AS, khususnya otomotif Menguntungkan produsen dalam negeri, tapi mempersulit ekspor negara tetangga seperti Meksiko
4 Penetapan Tarif Baja dan Aluminium (Section 232) Tarif hingga 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium dari negara mitra dagang Mengurangi impor bahan baku industri, memicu balasan tarif dari Uni Eropa dan Tiongkok
5 Pemberlakuan Sanksi Ekonomi dan Pembatasan Teknologi Pembatasan ekspor teknologi ke perusahaan seperti Huawei Memperkuat tensi geopolitik dan memicu ketidakpastian di sektor teknologi global.
Perspektif Literatur Kebijakan
Dari sisi kajian literatur apa dampak perang tarif yang di tabuh oleh Amerika Serikat bagi pembanguan berkelanjutan ? dalam beberapa perspektif sosiologi ekonomi, ekonomi politik, dan pembangunan berkelanjutan.
Beberapa temuan penting dari literatur yang relevan antara lain: Perang Dagang dan Ketimpangan Struktural ; Menurut Bown dan Irwin (2019), perang dagang cenderung memperkuat dominasi negara-negara kuat dan melemahkan posisi negara berkembang dalam rantai pasok global. Efek domino yang ditimbulkan tidak hanya memperlambat arus perdagangan, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan meningkatkan kerentanan kelompok rentan. SDGs dalam Ancaman Global; Laporan tahunan SDGs (Sachs et al., 2022) menyoroti bahwa ketegangan geopolitik dan krisis ekonomi global memperlambat pencapaian target SDGs, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan layak (SDG 8), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10).
Ancaman perang dagang dan ketahanan sosial; Kebijakan proteksionis yang diadopsi selama pemerintahan Trump memunculkan efek ketidakpastian global. Negara-negara yang bergantung pada ekspor mengalami disrupsi ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial.
Ketidakpastian ini juga memicu penurunan investasi sosial, berkurangnya layanan publik, dan melemahnya kohesi sosial di banyak wilayah. Perang dagang merupakan manifestasi dari dinamika kekuasaan dalam sistem ekonomi global.
Menurut Robert Gilpin (2001), kebijakan ekonomi suatu negara tidak pernah sepenuhnya bebas dari kepentingan geopolitik. Dalam kasus perang dagang AS–Tiongkok, Trump menggunakan kebijakan tarif sebagai alat tekanan terhadap dominasi ekonomi Tiongkok yang berkembang pesat. Bown dan Irwin (2019) menunjukkan bahwa kebijakan tarif tersebut mengubah arus dagang global dan meningkatkan ketidakpastian pasar, tidak hanya di negara yang terlibat langsung tetapi juga di negara-negara mitra yang terdampak secara tidak langsung.
Ekonomi Sosial Etis Muncul urgensi untuk mengeksplorasi model ekonomi alternatif yang lebih tangguh dan inklusif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah ekonomi berbasis sosial atau etis, yang menempatkan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan komunitas sebagai inti dari aktivitas ekonomi. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang terpusat pada profit dan ekspor, model ini mengedepankan penguatan ekonomi lokal, perdagangan adil, transparansi, serta keberlanjutan lingkungan. Ekonomi etis terbukti lebih resilien dalam menghadapi guncangan eksternal karena berakar pada solidaritas komunitas dan rantai pasok lokal yang lebih pendek. Selain itu, adanya tren global terhadap nilai-nilai ESG (Environmental, Social, and Governance) memberikan peluang pasar baru bagi produk-produk berbasis etika, terutama di kawasan Eropa dan Asia Timur. Dalam konteks Indonesia, ekonomi sosial dapat diimplementasikan melalui penguatan koperasi, bisnis sosial, dan UMKM berbasis komunitas yang tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial di tingkat local seperti Halal food, Halal Fishon. Oleh karena itu, ekonomi etis berpotensi menjadi salah satu strategi nasional dalam menghadapi gejolak ekonomi global, sekaligus mendorong transformasi menuju pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Konsep ekonomi berbasis nilai sosial yang menekankan keadilan, solidaritas, dan partisipasi masyarakat dianggap mampu memberikan solusi terhadap persoalan struktural. Model ini mendorong penguatan komunitas lokal, distribusi sumber daya yang adil, serta praktik ekonomi yang etis dan berkelanjutan (Laville, 2010; Utting, 2015).
Ekonomi halal yang mengedepankan prinsip thayyib (baik dan berkualitas) secara inheren terintegrasi dengan nilai-nilai ekonomi etis dan keberlanjutan.
Produk halal saat ini telah melampaui konteks religius dan menjadi standar baru dalam konsumsi global, terutama di pasar negara-negara OKI, Timur Tengah, dan bahkan di Eropa serta Asia Timur. Dengan permintaan global terhadap produk halal yang terus tumbuh, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki peluang besar untuk memimpin pasar ini melalui pendekatan berbasis nilai sosial dan keberlanjutan. Di tengah potensi disrupsi rantai pasok akibat perang dagang dan ketegangan geopolitik, ekonomi etis dan halal mendorong kemandirian produksi nasional, penguatan UMKM berbasis komunitas, dan peningkatan nilai tambah ekspor.
Kombinasi keduanya bukan hanya strategi mitigasi ekonomi, tetapi juga arah baru untuk membangun ekonomi yang tangguh, berdaya saing global, dan berbasis nilai. Oleh karena itu, pengarusutamaan ekonomi sosial-halal menjadi langkah krusial dalam membangun ekosistem ekonomi masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.
Oleh : Dr. H. Mohammad Syawaludin. MA
Dosen pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang





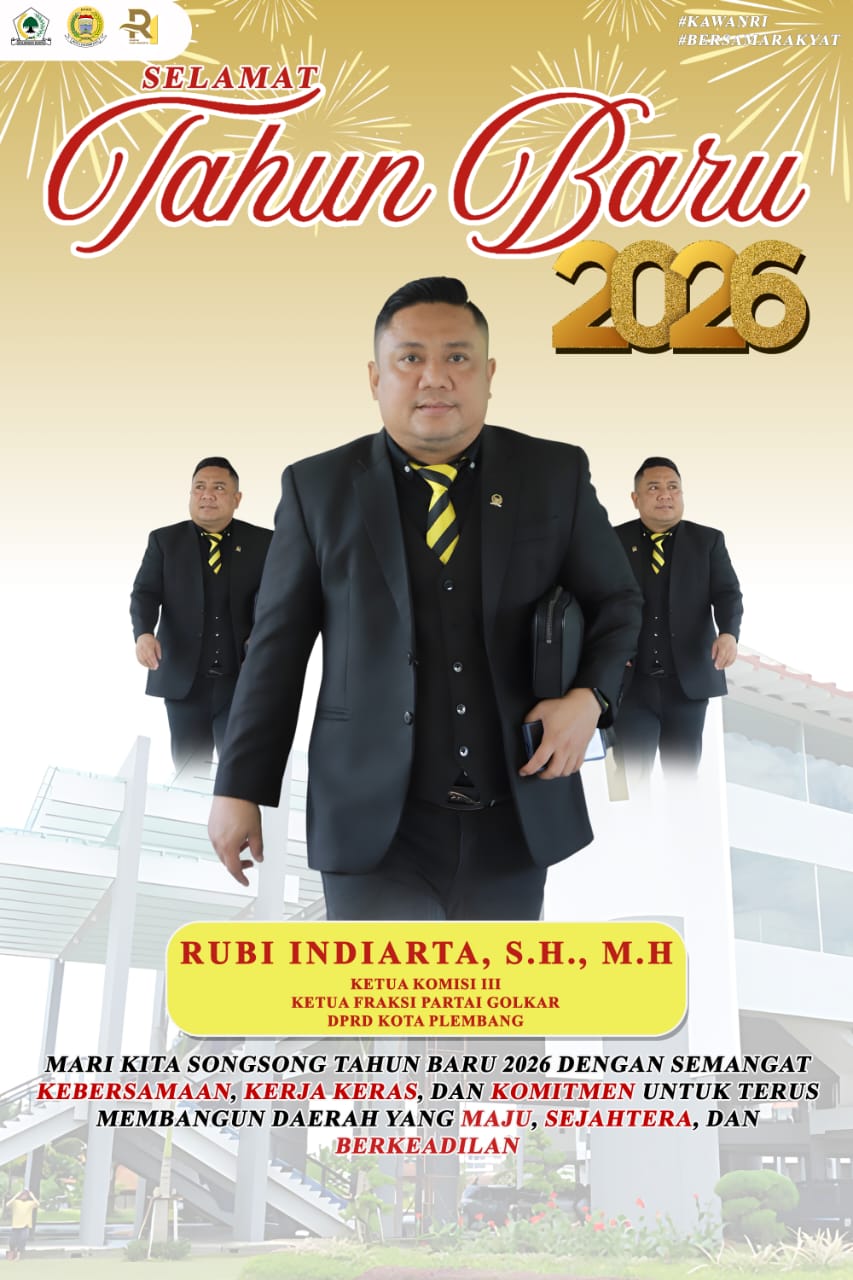








Komentar